Ayah Stephen Hinshaw, filsuf Virgil Hinshaw, Jr., dibesarkan di California, putra seorang ayah Pelarangan dan ibu misionaris dan ibu tiri (ibunya meninggal ketika dia berusia tiga tahun). Selama pertengahan 1930-an, ia menjadi terobsesi dengan gerakan fasis di seluruh dunia. Sebagai bagian dari episode manik pertamanya pada usia 16, dan sekarang sepenuhnya delusi, ia berusaha untuk terbang dari atap rumahnya. rumah keluarga, percaya bahwa lengannya telah menjadi sayap, untuk mengirim pesan kepada para pemimpin dunia untuk menghentikan Nazi. Dia selamat tetapi dirawat di rumah sakit secara brutal selama enam bulan berikutnya, memulai kehidupan yang cemerlang diselingi kegilaan. Bertahun-tahun kemudian, sebagai profesor di Ohio State, ia secara berkala menghilang (ketika dirawat di rumah sakit tanpa disengaja), tetapi dokternya memerintahkan agar anak-anak kecil, Steve dan Sally, tidak pernah diberitahu kebenaran tentang ketidakhadiran misterius ini, jangan sampai mereka dirusak secara permanen oleh pengetahuan. Rasa malu dan stigma di sekitarnya
Di sini, dalam kutipan dari memoarnya yang baru dirilis “Jenis Kegilaan Lain: Perjalanan Melalui Stigma dan Harapan Penyakit Mental“, Stephen menceritakan sepotong kisahnya.
Saya sekarang di kelas empat dan Ayah telah kembali selama beberapa bulan. Kerangka pikir saya lebih baik dari tahun sebelumnya selama ketidakhadirannya yang tampaknya tak ada habisnya.
Pada suatu sore musim gugur yang sejuk, dia menarikku ke jalan masuk begitu dia tiba dari kampus. "Ulurkan tanganmu di depanmu," katanya, berhenti sementara aku mengangkat tanganku. "Itu dia, buat bola udara." Dia memulai semacam pelajaran sains, mungkin juga pelajaran yang lebih dalam. Dengan dia, sulit untuk mengatakannya. “Berapa banyak molekul udara, berapa banyak atom oksigen atau nitrogen yang menyusun molekul-molekul ini, menurut Anda ada di dalam tangan Anda? Bisakah kamu menebak?”
Saya tahu bahwa atom itu kecil. “Umm, mungkin jutaan?”
Ayah menggelengkan kepalanya. "Masih banyak lagi," jawabnya, ekspresi heran memenuhi matanya. “Jawabannya mungkin mendekati kuadriliun, bahkan triliunan. Membayangkan! Lebih dari butiran pasir di pantai yang luas, di banyak pantai.”
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagian besar atom adalah ruang kosong, nukleus dan elektron sangat kecil dibandingkan dengan area yang luas di antaranya, seperti planet yang mengorbit matahari. “Seperti yang dikatakan Einstein, nukleus itu seperti lalat di dalam katedral,” lanjut Ayah, duniaku sehari-hari sudah lama lenyap. “Dunia di sekitar kita penuh dengan keajaiban,” ia menyimpulkan, “di luar kemampuan pengamatan kita.”
Membuat obrolan ringan di pertemuan keluarga dengan ekspresi tegang, Ayah mungkin menjawab dengan sopan tentang cuaca atau apa yang mungkin disajikan untuk makan malam. Namun ketika berbicara tentang sains atau era yang berbeda dalam sejarah, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tenang. Satu versi dirinya sedikit hilang di laut, berjuang untuk mempertahankan kehadirannya di dunia yang dihuni semua orang, tetapi versi lainnya—bersemangat dan persuasif—mencari esensi keberadaan. Ketika saya memikirkan dua gayanya, rasa dingin menusuk tulang punggung saya, meskipun saya tidak bisa mengatakan mengapa …
Ibu sekarang jauh lebih sibuk, karena dia kembali ke Ohio State untuk mendapatkan gelar Master kedua dan kredensial mengajar, dengan tujuan mengajar bahasa Inggris dan sejarah kepada siswa sekolah menengah pertama. Di atas meja piknik di halaman belakang selama cuaca hangat, saya melihat Ayah duduk di sebelahnya saat mereka menjulurkan leher mereka di atas teks tentang tata bahasa transformasional dari kursus linguistiknya. Dengan sabar, dia menjelaskan seluk-beluk analisis Chomsky, diagramnya tampak seperti jaring laba-laba. Kepala dan dada mereka saling miring saat mereka berbagi konsentrasi yang dalam.
Saat itu, saya memusatkan perhatian pada landasan perencanaan, sekolah, dan atletik, membidik tepat di tengah. Seperti peta bumi datar abad pertengahan, dunia tidak lagi ada di luar batas-batas yang dikendalikan dari ketiga kegiatan itu. Di tempat lain yang tak terkatakan mengintai. Ada sesuatu yang menunggu di luar kendali hidupku, tapi aku tidak bisa membayangkan apa.
Waktu malam masih sulit. Kata-kata umpatan tidak muncul di benak saya seperti tahun sebelumnya, ketika Ayah pergi, tetapi saya khawatir jika saya tidak bisa tidur, saya akan sakit parah. Ketakutan itu menempel padaku seperti demam kronis.
Suatu malam di penghujung musim gugur saya tertidur dengan cepat tetapi di tengah malam duduk tegak, jantung saya berdebar kencang. Terkejut, dalam keadaan larut malam yang membingungkan, saya yakin bahwa saya tidak tidur sama sekali, diliputi oleh keyakinan bahwa jika saya berbaring di sana lebih lama lagi, jantung saya akan berhenti. Aku melompat turun dari ranjang atas, bergegas melintasi karpet, dan menggedor pintu kamar orang tuaku dengan keras. Aku seharusnya tetap diam untuk Sally, tidur di kamarnya di dekatnya, tapi aku tidak bisa menahannya.
"Mama! Ayah!" Aku berteriak, terisak. “Aku mulai sakit. Membantu!" Tidak ada Jawaban; Aku memukul sekali lagi. "Tolong bantu aku. aku mungkin akan mati.”
Setelah beberapa saat, saya mendengar suara bantalan lembut. Membuka pintu perlahan, Ayah mengintip keluar. Mengenakan piyama, matanya berbinar karena tidur, dia berbisik: "Ada apa?"
“Aku sudah bangun sepanjang malam. Saya tidak bisa tidur. Saya tidak berpikir saya bisa hidup. ”
Dia berhenti, berbalik, dan berbicara dengan lembut ke arah Ibu. Kemudian, memberi isyarat agar saya memimpin, dia mengikuti saya kembali ke kamar tidur saya. Setelah aku menaiki tangga ke tempat tidurku, dia mengusap dahiku. "Ceritakan lagi apa yang mengganggumu," tanyanya pelan.
Setengah tersedak, aku mengatakannya. “Saya terjaga sepanjang malam; Saya tidak bisa tidur. Aku bisa mati besok pagi.” Aku mulai menangis lagi.
Dia merenung sejenak. "Tidak perlu khawatir," katanya dengan tenang tetapi dengan keyakinan. “Cukup istirahat membantu tubuh Anda; mungkin 70 persen sama baiknya dengan tidur.” Mengambil kekuatan, lanjutnya.
“Anda mungkin tidak mengetahuinya, Steve, tetapi Anda hidup di zaman keajaiban. Bahkan jika Anda jatuh sakit, dokter sekarang dapat mengobati banyak penyakit dengan obat-obatan baru.” Saat masih kecil, lanjutnya, antibiotik dan obat-obatan lain saat ini belum ada. Banyak orang meninggal, beberapa sangat muda. Dia mengingatkan saya bahwa paman buyut saya Corwin ada di tim peneliti yang menemukan mekanisme antibiotik untuk mengobati tuberkulosis.
“Bayangkan waktu sebelum obat-obatan seperti itu,” lanjutnya, “tingkat kematiannya tragis.”
Dia menyimpulkan: “Mengapa, dengan kemajuan yang dibuat hari ini — dengan keajaiban pengobatan modern ini — jika Anda merawat diri sendiri dengan baik, Anda mungkin akan hidup sampai 100 tahun. tahun!” Dalam sekejap langit-langit ditarik, seperti yang di atas astronom dalam gambar kelas satu saya, cahaya bintang mengalir dari observatorium pembukaan. Seratus tahun!
Ayah mulai berbicara tentang penemuan tambahan tetapi saya sudah mulai melayang. Dia segera mengucapkan selamat malam dan berjalan kembali melintasi karpet. Hampir tertidur, aku menyimpan nomor itu di pikiranku. Bukan keabadian, mungkin, tetapi 100 tahun tampaknya rentang yang luas.
Sebagai orang dewasa saya mulai mempertimbangkan minat ayah saya pada keajaiban pengobatan modern yang dia gambarkan. Tidak diragukan lagi, dia bertanya-tanya mengapa tidak ada mukjizat seperti itu yang pernah tersedia baginya. Mengapa episode misteriusnya begitu tak terduga, begitu memalukan—dan begitu jauh dari perawatan medis yang memuaskan? Dia merasa, seperti yang dia katakan kepada saya di tahun-tahun terakhirnya, bahwa tidak ada yang mengerti penderitaannya dan bahwa dia bahkan tidak pantas mendapatkan bantuan.
Ketika individu termasuk dalam kelompok yang menerima stigma kuat dan mau tidak mau mendengar pesan masyarakat tentang kelompok mereka, ada kemungkinan besar mereka akan menyerap konten yang mendasarinya. Dengan kata lain, stigma sosial berubah menjadi stigma diri, menyelesaikan lingkaran setan. Stigma yang terinternalisasi seperti itu—pandangan bahwa seseorang pada dasarnya cacat dan tidak layak—membawa konsekuensi yang menghancurkan.
Sudah cukup buruk untuk menjadi bagian dari kelompok di luar arus utama. Tetapi ketika individu-individu yakin bahwa kelemahan dan kegagalan moral mereka sendiri adalah akar dari masalah, segalanya akan berakhir. Tidak mengherankan, dalam kasus penyakit mental, tingkat stigma diri yang tinggi memprediksi kegagalan untuk mencari pengobatan, atau putus sekolah lebih awal jika pengobatan benar-benar dimulai.
Tidak semua anggota kelompok yang terstigma menunjukkan stigma diri. Meskipun prasangka dan bias rasial masih ada, banyak anggota kelompok minoritas rasial di Amerika Serikat memiliki tingkat harga diri yang sehat. Faktor protektif adalah solidaritas dan identifikasi positif dengan anggota kelompok lainnya. Pikirkan Kekuatan Hitam, kebanggaan gay, atau gerakan perempuan, yang dapat menggagalkan identifikasi negatif sambil mempromosikan advokasi dan harga diri yang positif.
Tetapi sampai baru-baru ini, siapa yang ingin mengidentifikasi diri dengan kelompok yang, menurut definisi, gila, gila, atau psiko? Isolasi dan rasa malu yang terkait dengan penyakit mental melanggengkan stigma yang terinternalisasi, yang pada gilirannya mendorong lebih banyak keputusasaan. Kelompok dan gerakan swadaya tidak ada di zaman Ayah, tetapi hari ini mereka adalah bagian utama dari lanskap kesehatan mental. Meskipun mereka sendiri tidak dapat menghapus stigma publik atau stigma diri, mereka adalah bagian dari solusi.
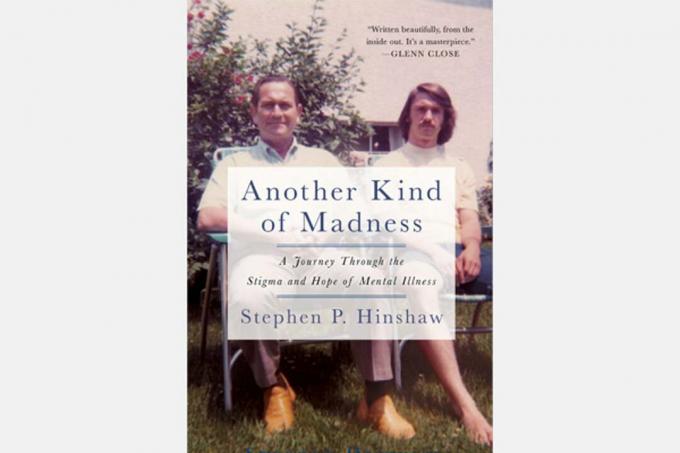
Dikutip dari JENIS KEGIATAN LAIN: Perjalanan Melalui Stigma dan Harapan Penyakit Mentaloleh Stephen Hinshaw Hak Cipta © 2019 oleh penulis dan dicetak ulang dengan izin dari St. Martin's Press, LLC.

